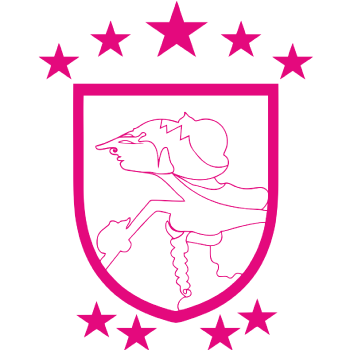Konstruksi sosial budaya yang notabene telah terinternalisasi di dalam masyarakat menjadi suatu keharusan untuk dijalani. Apabila salah satu diantara kita meninggalkannya maka akan memberikan penilaian bahwa kita merupakan manusia yang tidak lazim, aneh, gila, dan bahkan dijauhi atau mendapat perilaku yang terbilang diskriminatif dari masyarakat. Hal-hal yang demikian juga berkorelasi terhadap situasi yang erat kaitannya dengan fenomena akan isu gender dan seksualitas. Salah satu fenomena seperti memilih untuk free marriage sampai saat ini masih menjadi isu yang seksi dan memecah masyarakat ke dalam dua bagian, yakni pro dan kontra. Pilihan untuk melajang seolah mendapat kecaman dari masyarakat, khususnya apabila pilihan ini diambil oleh seorang perempuan. Perempuan yang memilih untuk free marriage dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Hal yang lazim terjadi ketika seorang perempuan dilahirkan dan dibesarkan, proses pendidikan yang diberikan mempersiapkan perempuan untuk kelak nantinya menjadi istri dan juga ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Contohnya, anak perempuan cenderung lebih besar posibilitasnya untuk terlibat dengan urusan bantu-membantu di dapur atau yang terlibat dengan urusan-urusan domestik yang lain, seperti beres-beres dan bersih-bersih rumah. Perempuan kerap kali dituntut bangun lebih pagi dan cekatan untuk mempersiapkan berbagai hal dengan anggapan sebagai ajang persiapan sebelum berumah tangga nanti. Pola yang demikian terus diulang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Hal ini tentu saja menekan dan membelenggu perempuan untuk bebas memilih apa yang diinginkannya hanya karena kentalnya paham mengenai doktrinasi ibuisme. Ditambah lagi, konstruksi masyarakat yang menetapkan usia minimal seorang perempuan untuk menikah semakin memperumit keadaan perempuan untuk berfokus pada hal-hal lainnya, seperti karir, pendidikan, ataupun eksplor diri.
Masyarakat khususnya di Indonesia juga tidak luput memberikan label bagi perempuan lajang berdasarkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya objektif-toksik. Masyarakat dominan melabeli perempuan yang demikian dengan istilah “Perawan Tua” atau “Perempuan Tidak Laku”. Asumsi dan dugaan bahwa mereka tidak laku karena misalnya, sudah tidak perawan, tidak bisa mengurus urusan rumah tangga, memiliki pemikiran yang terlalu liberal, perempuan modern yang sulit nantinya untuk diatur atau ditundukkan oleh suami, dan dianggap introvert karena tidak bisa bergaul atau mencari pasangan kerap kali digaungkan sebagian besar masyarakat kita. Pola pemikiran masyarakat yang demikian memberikan asumsi tidak berdasar tanpa tahu latar belakang seorang perempuan memilih melajang, misalnya saja karena adanya hal lain yang diprioritaskan. Banyak keluarga dari perempuan yang memilih free marriage juga terkesan tidak mendukung keputusan tersebut dan malu atau bahkan menyalahkan keputusan anak perempuannya. Perempuan juga seolah dijadikan komoditas, situasi dimana semakin bertambah usia seorang perempuan maka nilai jualnya diasumsikan semakin rendah. Menariknya, hal-hal yang demikian justru jarang ditemui ketika aktornya adalah seorang laki-laki. Laki-laki memiliki hak istimewa dan posisi yang lebih tinggi untuk memiliki kelonggaran dalam memilih melajang atau menikah di usia yang menurut masyarakat sudah tidak muda lagi. Hal lain yang ditemui adalah pujian dari sebagian masyarakat karena keputusan laki-laki menunda atau tidak menikah karena karir diasumsikan sebagai pilihan yang tepat karena mendahulukan kualitas ekonominya agar bisa membangun keluarga di masa depan atau dianggap “Pria Idaman” karena memiliki sifat pekerja keras. Jelas terlihat bahwa tekanan serta stigma negatif dari masyarakat dominan ketika memilih free marriage atau melajang seumur hidup lebih besar ditujukan kepada perempuan ketimbang laki-laki.
Adanya diskriminasi dan stigma negatif yang diberikan khususnya kepada perempuan yang memilih free marriage dikarenakan masyarakat Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat Asia direpresentasikan memiliki kecenderungan kolektivis yang lebih kental dibanding masyarakat Amerika dan Eropa. (Markus & Kitayama, 1991; Matsumoto, 2004 dalam Septiyana & Syafiq, 2013). Dengan demikian, anggota masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan yang jauh lebih besar untuk mempertahankan norma budayanya, seperti pernikahan. Pernikahan itu sendiri merupakan salah satu ritus budaya yang sangat dihargai oleh hampir semua kelompok etnis dan budaya di Indonesia serta setiap orang dianjurkan untuk menjalani tahap pernikahan disaat mereka telah dewasa. Oleh karena itu, apabila ditemui orang dewasa, khususnya perempuan belum menikah dan tinggal dalam budaya yang mengharapkan perempuan menikah, mereka akan mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk orang tua dan teman-temannya untuk segera menikah (Hurlock, 1980 dalam Septiyana & Syafiq, 2013). Menilik lebih jauh melalui perspektif gender, faktor lain yang mendasari munculnya stigma buruk terhadap perempuan yang memilih untuk free marriage adalah hegemoni patriarki yang pada dasarnya tanpa sadar diwariskan secara turun temurun antar generasi. Hadirnya budaya patriarkis pada masyarakat Indonesia menuntut perempuan untuk menjadi ibu dan istri dalam sebuah keluarga agar kehadirannya dihargai secara penuh sebagai anggota atau bagian dari sebuah masyarakat. Oleh karena itu, keharusan menikah dan apabila menikah menjadi sesuatu yang ditinggalkan, perempuan belum dianggap sepenuhnya sebagai sosok perempuan yang lengkap. Kebebasan, kemandirian, atau menjadi perempuan profesional yang menghabiskan waktunya untuk karir dan hal-hal selain pernikahan tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Sebagian besar dari masyarakat kita yang menganut pemahaman yang dominan seperti keharusan menikah bagi perempuan, tidak mampu membuka diri dan menerima arus perubahan karena banyak faktor, seperti kurangnya pendidikan yang menjadikan perempuan mampu berfikir secara logis dan sadar bahwa ketika mereka menikah ada banyak masalah serta beban yang kemudian hanya diberikan ke perempuan, misalnya seperti beban ganda dalam pekerjaan dan urusan domestik.
Diskriminasi dan stigma stigma yang diberikan masyarakat dominan kepada perempuan yang memilih free marriage mengakibatkan goncangan psikologis, seperti banyak perempuan single merasa tertekan, risih, tidak nyaman, dan merasa kesepian (Septiyana & Syafiq, 2013). Pada dasarnya, solusi yang seharusnya hadir atas fenomena ini adalah memutus akar yang menjadi penyebab masalah ini, yakni memerangi hegemoni patriarki yang sebenarnya bisa dikatakan tertanam dalam nilai-nilai yang dianut masyarakat kita. Akan tetapi, pada realitanya, mengontrol hal-hal yang sifatnya eksternal jauh lebih sulit ketimbang mengontrol hal-hal yang sifatnya internal atau berasal dari dalam diri sendiri. Untuk itu, sebagai perempuan khususnya, harus bisa berdaulat atas diri mereka sendiri tanpa ada tekanan dari lingkungan sekitar, untuk itu literasi dan pendidikan agar mampu menjadi sosok perempuan yang kritis dan sadar mengenai apa yang menjadi kebutuhan dan prioritasnya perlu ditekankan. Selain itu, proses internalisasi nilai-nilai khususnya dalam keluarga sebagai institusi terkecil dan proses pendidikan sebelum memasuki dunia luar perlu diubah. Anak-anak perempuan dilahirkan dan dibesarkan bukan dengan narasi untuk kelak nantinya menjadi istri orang lain dan juga seorang ibu, melainkan menjadi manusia utuh dengan pribadi yang mandiri, bebas, cerdas, dan mampu memilih apa yang menjadi prioritasnya. Begitupun dengan kurikulum pendidikan yang umumnya bias gender, juga perlu mengalami revisi. Jadi, perempuan tidak lagi dikontrol oleh konstruksi masyarakat yang patriarkis. Kemudian, pada akhirnya, kelajangan atau keputusan free marriage bagi perempuan dimaknai sebagai sesuatu yang tidak negatif lagi untuk kedepannya dan tercipta lingkungan yang benar-benar ramah ataupun aman bagi perempuan dengan segala keputusannya.
Daftar Pustaka
Himawan, K. K., Bambling, M., & Edirippulige, S. (2018). What Does It Mean to Be Single in Indonesia? Religiosity, Social Stigma, and Marital Status Among Never-Married Indonesian Adults. SAGE Open, 8(3). https://doi.org/10.1177/2158244018803132
Intan, T. (2021). Perempuan Lajang dan Perjodohan dalam Novel “Jodoh Terakhir” Karya Netty Virgiantini. Alinea: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajaran, 10(1), 1. https://doi.org/10.35194/alinea.v10i1.1093
Intan, T., & Prayoga, E. A. (2021). Strategi Kebertahanan Perempuan Lajang dalam Novel Cincin Separuh Hati Karya Netty Virgiantini. Jurnal Ilmiah FONEMA : Jurnal Edukasi Bahasa Dan Sastra Indonesia, 4(1), 1. https://doi.org/10.25139/fn.v4i1.3227
Purwanto, E. (2015). Pengaruh bibliotherapy terhadap psychological well-being perempuan lajang. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 4(1), 1–26.
Septiana, E., & Syafiq, M. (2013). Identitas “Lajang” (Single Identity) Dan Stigma: Studi Fenomenologi Perempuan Lajang Di Surabaya. Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan, 4(1), 71. https://doi.org/10.26740/jptt.v4n1.p71-86